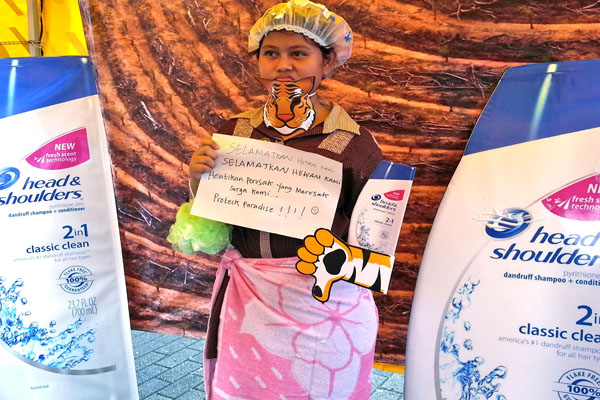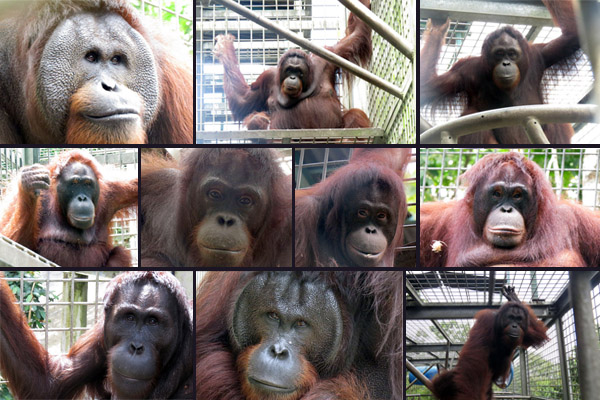Landscape Hutan Harapan Jambi, Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia. Foto: Fahrul Amama/ Burung Indonesia
Dogma lama bahwa hutan adalah penyedia kayu telah menjadikan hutan di
Indonesia rusak parah. Tidak saja kerugian ekonomi yang terjadi, namun
kerugian sosial, potensi hilangnya jasa lingkungan dan keragaman
hayati. Pengelolaan di hutan produksi harusnya bukan untuk kayu semata
tetapi tetapi harus meliputi prinsip keberlanjutan, produktivitas,
konektivitas, keaslian dan keragaman hayati.
Koreksi terhadap pengelolaan hutan produksi dari komoditas kayu, saat
ini coba dilakukan melalui perbaikan yang dikenal dengan upaya
Restorasi Ekosistem di wilayah hutan produksi yang diatur lewat Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
Jika hutan konservasi dikelola oleh pemerintah, maka Restorasi Ekosistem
(RE) akan dilakukan oleh swasta yang berminat.
Kegiatan IUPHHK-RE bertujuan untuk mengembalikan unsur hayati (flora
dan fauna) serta non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu
kawasan kepada jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan
ekosistemnya. Demikian pula, RE merupakan upaya untuk mempertahankan
fungsi dan keterwakilan ekosistem hutan alam melalui kegiatan
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan.
Hingga Maret 2014, ijin RE telah dikeluarkan kepada 12 perusahaan
dengan cakupan luasan 480.093 ha. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, IUPHHK-RE mendapat alokasi
seluas 2.695.026 hektar. Ijin RE pertama di Indonesia yang dikenal
dengan nama Hutan Harapan sendiri telah berjalan Konsorsium Burung
Indonesia di Sumatera Selatan sejak tahun 2007.
“Hal positif dari RE adalah akan tercipta pengembangan usaha multi
produk dan jasa serta laju deforestasi dan emisi karbon dari hutan
produksi berkurang,” ungkap Mangarah Silalahi, Kepala Resource Center
Pengembangan Restorasi Ekosistem Burung Indonesia.
Menurutnya pengelolaan IUPHHK-RE harus didukung karena sangat
berpeluang untuk mempertahankan konektivitas bentang hutan alam dan
mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.
Perambahan
kawasan, salah satu masalah di area restorasi ekosistem. Skema
Restorasi Ekosistem harus memikirkan upaya penyelesaian konflik dan
masalah sosial. Foto: Aulia Erlanga/ Burung Indonesia
Tantangan Restorasi Ekosistem
Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Hutan dari Institut
Pertanian Bogor menyebutkan bahwa keberadaan RE bukannya tanpa
hambatan. Menurut Hariadi, masalah restorasi ekosistem saat ini bukan
lagi melulu masalah teknis kehutanan seperti penanaman dan pemiliharaan
tetapi yang lebih penting adalah menempatakan persoalan sosial.
Pengelolaan hutan harus berubah dari definisi fisik ke interaksi
sosial dan pola ruang. Sehingga solusinya dengan demikian harus mencari
model usaha yang kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan.
“Hal utama dari restorasi ekosistem berada di tingkat manajemen
unit. Jika penetapan lokasi ijin tumpang tindih, maka akan timbul
konflik sosial. Masalah tata batas krusial supaya tidak timbul konflik.
Jangan lagi nanti kampung orang masuk ke dalam kawasan konsesi.”
Hariadi juga menyoroti masalah penggunaan peta indikatif. Menurutnya
peta 1:100.000 yang selama ini dipakai di Kehutanan tidak lagi layak,
seharusnya peta yang digunakan adalah peta 1:50.000 atau 1:25.000 sesuai
dengan pertimbangan teknis dari Gubernur/ Bupati yang setara dengan
skala peta Hak Guna Usaha (HGU).
“Harus juga diingat sekarang dengan adanya keputusan MK 35/2012
kawasan hutan itu bukan lagi semuanya adalah kawasan hutan negara,
selain hutan negara juga ada hutan hak dan hutan adat,” ujarnya
menambahkan.

Demikian pula jika RE diharapkan akan eksis tanpa melakukan
eksploitasi kayu, maka perlu dicarikan skema struktur finansial yang
tepat dan sumber pembiayaan yang tepat. Bagi para pelaku usaha maka
diperlukan suatu aspek kepastian usaha dalam pemanfaatan hutan produksi
yang mencakup kepastian kawasan, waktu dan jaminan hukum.
“Termasuk harusnya ada insentif kebijakan bagi pelaku usaha RE”
menurut Sukianto Lusli dari Konsorsium Burung yang sekarang sedang
mengurus ijin IUPHHK-RE di Gorontalo.
Menurutnya akan berat jika ijin RE disamakan dengan pengelolaan kayu.
Literatur dan paradigma lama, termasuk aturan regulasi yang berlaku
untuk HPH sudah harus direvisi agar cocok bagi pengelolaan RE. Tanpa
adanya eksploitasi ekstraktif seperti kayu, bahkan malahan mengeluarkan
dana investasi untuk restorasi, maka perhitungan ekonomi seperti Return on Investment (RoI) dalam paradigma lama tidak akan cocok dalam skema bisnis RE yang amat jauh berbeda.
Berbeda dengan IUPHHK-HA (Hutan Alam) yang memiliki maksimum ijin 55
tahun, maka IUPHHK-RE memiliki konsesi hingga 60 tahun dan dapat
diperpanjang hingga 35 tahun.
Para pelaku juga meminta pemerintah agar lokasi yang dicadangkan
untuk RE berada dalam lokasi yang strategis, tidak terpisah dan tidak
berada dalam kawasan yang sulit dijangkau, termasuk potensi konflik yang
dapat diatasi. Para pelaku pun menyoroti masalah ekonomi biaya tinggi
yang kerap terjadi dalam pengusahaan kehutanan.
Dalam proses pengelolaan RE, jika keseimbangan hayati telah tercapai
maka pemerintah juga harus harus membuka peluang bagi pemegang konsesi
untuk berbagai pemanfaatan hasil hutan dan tidak diharuskan kembali ke
kayu.
Bagi para pelaku RE, peluang pendanaan pengelolaan dapat berasal dari
peluang internasional untuk pembayaran kompensasi biaya karbon.
Pemerintah diharapkan dapat keluar dengan kebijakan yang dapat
memudahkan aliran skema finansial untuk mengambil peluang ini.
Source : link
Source : link